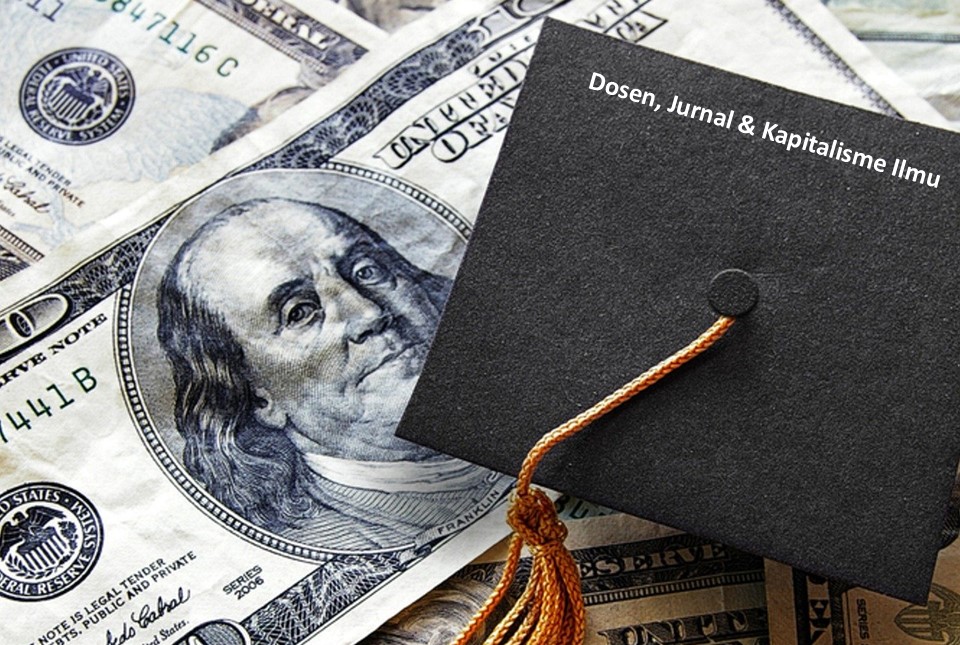Oleh: Rudi Trianto – Mahasiswa Pascasarjana Program Doktoral (S3) UIN Walisongo Semarang
Dosen, Jurnal, dan Kapitalisme Ilmu: Saat Pikiran Harus Berbayar. Dunia akademik saat ini bukan lagi sekadar tempat mencari makna, tapi sudah menjadi ruang dagang yang ramai dengan tarif, algoritma, dan target pasar. Ilmu pengetahuan yang dulunya bebas dibagikan, kini harus dibayar mahal untuk ditulis dan dibaca. Banyak penulis muda dengan gagasan kuat harus tersingkir hanya karena tak mampu membayar biaya publikasi yang tinggi, sementara penerbit besar terus mengeruk untung. Lalu, bagaimana nasib ilmu pengetahuan jika yang diutamakan bukan lagi isi, tetapi siapa yang mampu membayar agar terdengar?
Daftar Isi
Pengetahuan Kini Harus Membayar untuk Didengar
Di dunia akademik saat ini, akses terhadap ilmu pengetahuan tak lagi setara. Menulis artikel ilmiah bukan cuma soal kemampuan berpikir, tapi juga soal kesiapan membayar. Bahkan untuk bisa membaca hasil riset pun, pembaca sering kali harus membayar biaya langganan yang tidak murah. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah ilmu pengetahuan masih menjadi milik publik, atau hanya milik mereka yang mampu?
Fenomena ini muncul seiring dengan meningkatnya tuntutan publikasi di jurnal internasional bereputasi sebagai syarat kenaikan jabatan fungsional dosen. Sistem ini menciptakan pasar akademik yang tidak ramah bagi mereka yang tak punya dana, terutama dosen-dosen muda dan peneliti dari kampus kecil. Artikel yang berkualitas bisa tidak terbit hanya karena penulisnya tak mampu membayar biaya publikasi, yang bisa mencapai jutaan rupiah per artikel. Ironisnya, jurnal-jurnal tersebut seringkali dikelola oleh penerbit raksasa yang meraih untung besar dari karya-karya ilmiah yang ditulis secara sukarela.
Baca juga: Followers, Persepsi, dan Viralitas: Tiga Tuhan Baru di Dunia Digital
Ambil contoh, banyak dosen Indonesia terpaksa menggunakan dana pribadi demi bisa memenuhi tuntutan ini. Mereka membayar untuk menulis, tapi tulisan mereka belum tentu bisa dibaca oleh publik karena dibatasi oleh paywall. Praktik ini mengunci ilmu di balik sistem ekonomi yang ketat. Di sisi lain, ini menunjukkan bagaimana ilmu berubah dari sarana pencerdasan menjadi komoditas elit.
Jika situasi ini dibiarkan, kita akan menciptakan kesenjangan akademik yang makin lebar. Pengetahuan akan menjadi barang mewah, bukan alat pemerdeka. Oleh karena itu, perlu ada gerakan bersama untuk mendorong akses terbuka dan sistem pendanaan yang adil bagi publikasi ilmiah, agar suara akademisi tidak hanya terdengar oleh yang membayar, tetapi juga oleh masyarakat luas yang membutuhkannya.

Dosen, Jurnal, dan Kapitalisme Ilmu Saat Pikiran Harus Berbayar
Birokrasi Menjepit, Akademisi Tercekik
Di balik semarak publikasi ilmiah yang terus digaungkan, tersembunyi beban berat yang dipikul para dosen dan peneliti. Mereka tidak hanya dituntut untuk mengajar, membimbing, dan meneliti, tetapi juga mengejar angka: berapa artikel yang terbit, berapa sitasi yang didapat, dan berapa indeks yang berhasil dicapai. Angka-angka ini bukan hanya sekadar statistik, tapi telah menjadi pengukur utama kinerja mereka.
Mengapa ini jadi masalah? Karena obsesi terhadap metrik dan sistem akreditasi justru menumpulkan daya kritis. Banyak akademisi akhirnya menulis bukan karena ingin mencari kebenaran atau menjawab persoalan masyarakat, tapi demi memenuhi syarat administratif. Akibatnya, lahirlah jurnal yang dipenuhi tulisan yang asal jadi: tidak dibaca, tidak berdampak, hanya demi satu tujuan—naik jabatan atau mempertahankan status.
Banyak dari mereka terjebak dalam siklus birokrasi yang melelahkan. Tenggat waktu pengisian BKD (Beban Kerja Dosen), target minimal publikasi per semester, hingga tekanan akreditasi institusi, semua berpadu dalam satu sistem yang menjadikan ilmuwan lebih mirip operator administrasi daripada pemikir bebas. Dalam kondisi ini, kreativitas sulit tumbuh, dan ruang refleksi ilmiah makin sempit.
Jika sistem ini terus dipertahankan, dunia akademik hanya akan menjadi pabrik produksi angka—bukan tempat pertumbuhan ide. Ironisnya, kampus yang seharusnya menjadi rumah bagi nalar justru menjadi mesin evaluasi yang dingin. Di tengah tekanan seperti ini, banyak akademisi memilih diam, menghindar, atau bahkan meninggalkan dunia riset karena kehilangan makna.
Komodifikasi Pikiran dan Hilangnya Etika Ilmu
Ketika segala hal diukur dengan untung-rugi, pikiran pun tak luput dari logika pasar. Di era ini, ide bisa dijual, opini bisa disponsori, dan artikel ilmiah bisa menjadi alat promosi. Inilah wajah baru pengetahuan: bukan lagi alat pembebasan, tetapi komoditas yang dijajakan. Dalam iklim seperti ini, etika keilmuan perlahan luntur, digantikan oleh kalkulasi dan strategi branding.
Masalahnya bukan pada publikasi itu sendiri, tapi pada sistem yang menjadikan ilmu sebagai alat pengumpul kapital. Banyak institusi pendidikan tinggi mendorong dosen untuk menulis demi menaikkan reputasi kampus, bukan untuk menjawab persoalan masyarakat. Yang penting terbit di jurnal bereputasi, urusan manfaat bisa belakangan. Bahkan terkadang, penulis utama hanya menjadi simbol, sementara isi tulisan dikerjakan oleh pihak lain.
Baca juga: Kampanye Politik Antara Rayuan Persuasif dan Serangan Black Campaign
Praktik semacam ini tidak hanya merusak integritas akademik, tetapi juga merendahkan martabat ilmu itu sendiri. Gagasan bukan lagi hasil perenungan dan proses intelektual, melainkan hasil proyek cepat yang harus selesai sebelum deadline. Bahkan dalam beberapa kasus, muncul tawaran jasa penulisan artikel ilmiah lengkap dengan jaminan terbit—ini bukan lagi dunia ilmu, melainkan pasar jasa.
Jika semua ini dianggap normal, kita akan sampai pada titik di mana pengetahuan kehilangan jiwanya. Ia tidak lagi menyinari, tapi menjual cahaya kepada yang mampu membeli. Maka, sudah saatnya kita bertanya: benarkah kita menulis untuk kebenaran, atau sekadar untuk terlihat berjasa? Jika tidak dikembalikan pada etika, dunia akademik hanya akan menjadi panggung sandiwara, bukan tempat lahirnya kebenaran.
Membangun Ekosistem Ilmu yang Etis dan Setara
Di tengah derasnya arus komersialisasi dan tekanan birokrasi dalam dunia akademik, muncul harapan akan sistem yang lebih adil, sehat, dan manusiawi. Dunia ilmu seharusnya bukan tempat menjual pikiran, melainkan ruang yang memungkinkan setiap orang berpikir bebas dan menyampaikan gagasannya. Kita memerlukan model ekosistem baru yang tidak menempatkan uang dan angka sebagai satu-satunya tolok ukur keberhasilan ilmiah. Solusi bukan berarti menolak kemajuan, tapi mengarahkan sistem agar tetap menghargai nilai-nilai luhur keilmuan.
Salah satu langkah penting adalah memperkuat penerbitan ilmiah berbasis akses terbuka non-komersial yang dikelola oleh universitas, lembaga riset, atau asosiasi ilmiah. Dengan cara ini, penulis tidak lagi terbebani biaya tinggi, dan masyarakat luas bisa membaca hasil riset tanpa harus membayar mahal. Model ini sudah diterapkan oleh beberapa kampus dan jurnal independen, namun masih perlu dukungan dari negara. Jika pemerintah dan institusi pendidikan tinggi turut membiayai dan mengakui kredibilitas model ini, maka jalan publikasi akan terbuka lebih lebar.
Contoh nyata bisa dilihat pada berbagai jurnal open access berbasis universitas yang membebaskan biaya publikasi dan membuka akses luas bagi pembaca. Di sisi lain, ada jurnal bereputasi yang tetap mematok biaya tinggi dan membuat dosen di daerah tertinggal kesulitan ikut bersaing. Ketimpangan ini hanya bisa diatasi jika kita membangun model distribusi pengetahuan yang merata. Dukungan kebijakan dan insentif menjadi penting untuk menyeimbangkan medan tempur ilmiah yang kini timpang.
Maka dari itu, reformasi akademik harus dilakukan secara menyeluruh. Penilaian kinerja dosen sebaiknya mempertimbangkan dampak sosial dan kontribusi nyata, bukan sekadar angka sitasi. Etika akademik harus kembali ditegakkan, dengan mendorong kejujuran, kolaborasi, dan kepedulian terhadap masyarakat. Jika sistem ini berhasil dibangun, maka ilmu bisa tumbuh tanpa sekat, dan dunia akademik kembali menjadi tempat lahirnya pemikiran yang merdeka dan bermartabat.